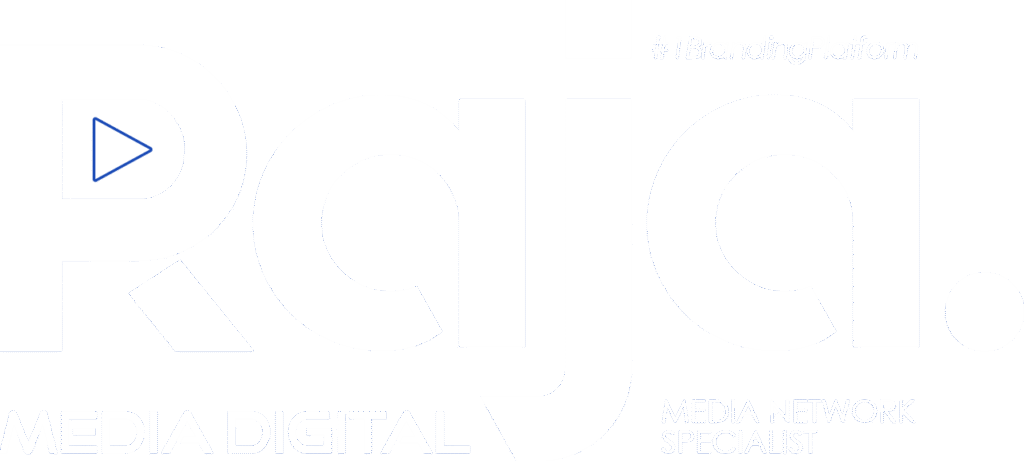Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, kembali menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan ekonomi Indonesia yang ia nilai gagal mengatasi deindustrialisasi dini dan membiarkan utang terus membengkak. Dalam catatan akhir tahunnya, ia menegaskan bahwa tanpa reformasi besar-besaran, ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% hanya akan menjadi sekadar ilusi politik tanpa dasar yang kuat.
Ia menggambarkan situasi sektor industri Indonesia saat ini sebagai kondisi yang “sekarat”. Selama bertahun-tahun, sektor ini hanya tumbuh pada kisaran 3 hingga 4 persen, angka yang jauh di bawah ekspektasi dan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah, menurut Didik, gagal memberikan perhatian serius terhadap revitalisasi sektor industri. Hal ini menyebabkan target pertumbuhan ekonomi 7% yang pernah dijanjikan pada era Presiden Joko Widodo meleset jauh. Lebih ironis lagi, jika tidak ada perubahan fundamental, wacana mencapai 8% di masa mendatang hanya akan menjadi retorika politik tanpa substansi.
Didik menilai bahwa deindustrialisasi dini menjadi akar permasalahan yang kian meruncing. Ia mengusulkan strategi reindustrialisasi berbasis sumber daya alam dengan orientasi ekspor, sebuah pendekatan yang sebelumnya terbukti sukses membawa Indonesia ke dalam jalur pertumbuhan ekonomi tinggi pada era 1980-an hingga awal 1990-an. Menurutnya, tanpa strategi industri berbasis sumber daya yang terintegrasi dengan pasar global, mustahil Indonesia dapat meraih pertumbuhan yang signifikan. Ia menyebut kondisi stagnasi saat ini sebagai tanda ketiadaan strategi besar yang mampu menjadi solusi jangka panjang.
Selain masalah industri, Didik juga menyoroti lonjakan utang pemerintah yang dianggap tidak terkendali. Berdasarkan data per September 2024, total utang Indonesia telah mencapai Rp8.473,90 triliun, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melonjak dari 26% pada tahun 2010 menjadi 38,55% pada tahun ini. Ia menggambarkan kondisi ini sebagai cerminan dari politik anggaran yang tidak sehat. Pemerintah, katanya, terlalu mudah mengambil utang dengan mengikuti teori “budget maximizer” tanpa mekanisme kontrol yang ketat.
Tingginya suku bunga obligasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lain menjadi sorotan utama dalam analisis Didik. Dengan bunga obligasi di kisaran 7,2%, Indonesia tercatat menawarkan suku bunga tertinggi di kawasan, jauh di atas Thailand yang hanya sebesar 2,7%, Vietnam 2,8%, dan Malaysia 3,9%. Kondisi ini, menurutnya, telah menjadi beban besar bagi rakyat. Setiap tahun, Indonesia harus mengalokasikan Rp441 triliun hanya untuk membayar bunga utang, angka yang mencerminkan biaya mahal dari kebijakan utang yang tidak terkendali.
Didik juga mengkritik pola belanja negara yang semakin tidak produktif. Peningkatan belanja nonproduktif, seperti belanja pegawai dan barang, dari 34% pada 2014 menjadi 36% pada 2024 mencerminkan prioritas yang keliru dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, belanja produktif terus mengalami penurunan, sebuah fenomena yang ia pandang sebagai ancaman serius bagi kesinambungan pembangunan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat ini tetapi juga akan menjadi warisan beban bagi pemerintahan di masa depan.
Diversifikasi pasar ekspor yang lamban turut menjadi perhatian utama. Indonesia dinilai masih terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Didik mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah agresif dalam membuka pasar baru di wilayah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin. Langkah ini, menurutnya, harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin keluar dari stagnasi neraca perdagangan yang kini membelenggu.
Dalam pernyataannya, Didik juga mengkritik keras janji-janji politik yang disampaikan tanpa strategi dan perencanaan yang jelas. Ia menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang menggantungkan harapan pada pengelolaan ekonomi yang lebih baik. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan reformasi struktural, terutama di sektor industri dan kebijakan fiskal. Tanpa itu, retorika ambisius hanya akan menjadi bayang-bayang kosong tanpa arah, sementara masalah yang ada terus berkembang menjadi krisis yang lebih mendalam.